Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani dan atau Latin politicos atau politicus yang berarti relating to citizen. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota.
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata politik sebagai “segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.” Juga dalam arti “kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani satu masalah).”
Dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata siyasah. Kata ini terambil dari akar kata sasa-yasusu yang biasa diartikan mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya. Dari akar kata yang sama ditemukan kata sus yang berarti penuh kuman, kutu, atau rusak.
Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata yang terbentuk dari akar kata sasa-yasusu, namun ini bukan berarti bahwa Al-Quran tidak menguraikan soal politik. Sekian banyak ulama Al-Quran yang menyusun karya ilmiah dalam bidang politik dengan menggunakan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sebagai rujukan. Bahkan Ibnu Taimiyah (1263-1328) menamai salah satu karya ilmiahnya dengan As-siyasah Asy-Syar’iyah (Politik Keagamaan).
Uraian Al-Quran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukm. Kata ini pada mulanya berarti “menghalangi atau melarang dalam rangka perbaikan”. Dari akar kata yang sama terbentuk kata hikmah yang pada mulanya berarti kendali. Makna ini sejalan dengan asal makna kata sasa-yasusu-sais siyasat, yang berarti mengemudi, mengendalikan, pengendali, dan cara pengendalian.
Hukm dalam bahasa Arab tidak selalu sama artinya dengan kata “hukum” dalam bahasa Indonesia yang oleh kamus dinyatakan antara lain berarti “putusan”. Dalam bahasa Arab kata ini berbentuk kata jadian, yang bisa mengandung berbagai makna, bukan hanya bisa digunakan dalam arti “pelaku hukum” atau diperlakukan atasnya hukum, tetapi juga ia dapat berarti perbuatan dan sifat. Sebagai “perbuatan” kata hukm berarti membuat atau menjalankan putusan, dan sebagai sifat yang menunjuk kepada sesuatu yang diputuskan. Kata tersebut jika dipahami sebagai “membuat atau menjalankan keputusan”, maka tentu pembuatan dan upaya menjalankan itu, baru dapat tergambar jika ada sekelompok yang terhadapnya berlaku hukum tersebut. Ini menghasilkan upaya politik.
Kata siyasat sebagaimana dikemukakan di atas diartikan dengan politik dan juga sebagaimana terbaca, sama dengan kata hikmat.
Di sisi lain terdapat persamaan makna antara pengertian kata hikmat dan politik. Sementara ulama mengartikan hikmat sebagai kebijaksanaan, atau kemampuan menangani satu masalah sehingga mendatangkan manfaat atau menghindarkan mudarat. Pengertian ini sejalan dengan makna kedua yang dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang arti politik, sebagaimana dikutip di atas.
Dalam Al-Quran ditemukan dua puluh kali kata hikmah, kesemuanya dalam konteks pujian. Salah satu di antaranya adalah surat Al-Baqarah (2): 269 :
Allah menganugrahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Qur’an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugrahi al hikmah itu, ia benar-benar telah dianugrahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).
WAWASAN POLITIK DALAM AL-QURAN
Dalam Al-Quran ditemukan sekian banyak ayat yang berbicara tentang hukm (Arab). Pengamatan sepintas, boleh jadi mengantarkan orang yang berkata, bahwa ada ayat Al-Quran yang secara tegas mengkhususkannya hanya kepada dan bersumber dari Allah yakni ayat yang menyatakan,
Katakanlah: “Sesungguhnya aku (berada)di atas hujjah yang nyata (Al Qur’an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan adzab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik. (tafsir QS Al-An’am [6]: 57).
Kelompok Khawarij yang tidak menyetujui kebiiaksanaan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib pernah mengangkat slogan yang bunyinya sama dengan redaksi penggalan ayat tersebut, tetapi ditanggapi oleh Ali r.a. dengan berkata,
“Kalimat yang benar, tetapi yang dimaksudkan adalah batil”.
Memang ada empat ayat Al-Quran yang menggunakan redaksi tersebut, tetapi ada dua hal yang harus digaris-bawahi dalam hubungan ini.
Pertama, keempat ayat yang menggunakan redaksi tersebut dikemukakan dalam konteks tertentu. Perhatikan ayat-ayat berikut:
Katakanlah: “Sesungguhnya aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kamu sembah selain Allah”. Katakanlah: “Aku tidak akan mengikuti hawa nafsumu, sungguh tersesatlah aku jika berbuat demikian dan tidaklah (pula) aku termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk”. Katakanlah: “Sesungguhnya aku (berada) di atas hujjah yang nyata (Al Qur’an) dari Tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah wewenangku (untuk menurunkan adzab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik. (Tafsir QS Al-An’am [6]: 56-57).
Ayat ini seperti terbaca berbicara dalam konteks ibadah serta keputusan menjatuhkan sanksi hukum yang berkaitan dengan wewenang Allah.
Dalam surat Yusuf (12):40,dan 67 redaksi serupa juga ditemukan ayat 40 berbicara dalam konteks mengesakan Allah dalam ibadah:
Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah) nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Menetapkan hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Tafsir QS Yusuf (12):40).
Sedangkan ayat 67 berbicara tentang kewajiban berusaha dan keterlibatan takdir Allah.
Dan Yakub berkata: “Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri”.(Tafsir QS Yusuf (12):67).
Ayat keempat dan terakhir menggunakan redaksi yang sedikit berbeda, yang terdapat dalam surat Al-An’am (6): 62,
Kemudian mereka (hamba Allah) dikembalikan kepada Allah, Penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah, bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaan-Nya. Dan Dialah Pembuat perhitungan yang paling cepat. (Tafsir QS Al-An’am (6):62).
Sebagaimana terbaca, ayat ini berbicara tentang ketetapan hukum yang sepenuhnya berada di tangan Allah sendiri pada hari kiamat.
Di sisi lain, ditemukan sekian banyak ayat yang menisbahkan hukum kepada manusia, baik dalam kedudukannya sebagai nabi maupun manusia biasa. Perhatikan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2):213 yang berbicara tentang diutusnya para nabi, dan diturunkannya kitab suci kepada mereka dengan tujuan, menurut redaksi Al-Quran:
Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (Tafsir QS Al-Baqarah (2):213).
Di samping perintah kepada nabi-nabi, ada juga perintah yang ditujukan kepada seluruh manusia yang berbunyi:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Tafsir QS Al-Nisa’ [4]: 58).
Kedua, kalaupun ayat-ayat yang berbicara tentang kekhususan Allah dalam menetapkan hukum atau kebijaksanaan, dipahami terlepas dari konteksnya, maka kekhususan tersebut bersifat relatif, atau apa yang diistilahkan oleh ulama-ulama Al-Quran dengan hashr idhafi. Dengan memperhatikan keseluruhan ayat-ayat yang berbicara tentang pengembalian keputusan, dapat disimpulkan bahwa Allah telah memberi wewenang kepada manusia untuk menetapkan kebijaksanaan atas dasar pelimpahan dari Allah SWT., dan karena itu manusia yang baik adalah yang memperhatikan kehendak pemberi wewenang itu.
KEKUASAAN POLITIK
Allah Swt. adalah pemilik segala sesuatu,
Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan: “Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya”. Katakanlah: “Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?” (Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya. Dan kepada Allah-lah kembali (segala sesuatu). (Tafsir QS Al-Ma-idah [5].
Demikian satu dan sekian banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu.
Benar, kita juga membaca,
(Alloh) Yang menguasai dan Pemilik hari kebangkitan (Tafsir QS Al-Fatihah [1]: 4).
Ayat ini boleh jadi mengantar seseorang untuk menduga bahwa Dia bukan pemilik hari-hari duniawi, namun ini tidaklah benar.
Ayat Al-Fatihah ini, menekankan bahwa kepemilikannya menyangkut hari kemudian adalah mutlak serta amat nyata, sehingga -ketika itu- jangankan bertindak, berbicara pun hanya berbisik:
pada hari itu manusia mengikuti (menuju kepada suara) penyeru dengan tidak berbelok-belok; dan merendahlah semua suara kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. (Tafsir QS Thaha [20]: 108).
Itu pun harus dengan seizin-Nya, jangankan manusia, malaikatpun demikian, seperti firman-Nya dalam surat Al-Naba’ (78):38.
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar. (Tafsir QS Al-Naba’ [78]:38)).
Adapun di dunia, maka di samping Dia melimpahkan sebagian kekuasaan-Nya kepada makhluk, juga karena kekuasaan tersebut tidak sejenis di hari kemudian. Bukankah masih ada manusia di dunia ini yang tidak mengakui kekuasaan Allah dalam perwujudan-Nya?
Dalam konteks kekuasaan politik, Al-Quran memerintahkan Nabi Muhammad Saw. untuk menyampaikan pernyataan tegas berikut:
Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.(Tafsir QS Ali Imran [3]: 26).
Dalam konteks ini, Rasul SAW. setiap habis shalat membaca doa, yang hingga kini masih populer di kalangan umat Islam:
Namun demikian, seperti tersurat dalam ayat di atas, Allah SWT menganugerahkan kepada manusia sebagian kekuasaan itu. Diantara mereka ada yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik karena mengikuti prinsip-prinsip kekuasaan politik dan ada pula yang gagal.
Paling tidak, dari dua istilah Al-Quran kita dapat menjumpai uraian tentang kekuasaan politik, serta tugas yang dibebankan Allah kepada manusia. Kedua istilah tersebut adalah istikhlaf dan isti’mar.
a. Istikhlaf
Dalam surat Al-Baqarah 2):30 dinyatakan
Sesungguhnya Aku (Allah) akan mengangkat di bumi khalifah.
Kata khalifah dalam bentuk tunggal terulang dalam Al-Quran sebanyak dua kali, yakni ayat di atas, dan surat Shad (38):26:
Wahai Daud Kami telah menjadikan engkau khalifah di bumi.
Bentuk jamak dari kata tersebut ada dua macam khulafa’ dan khalaif. Masing-masing mempunyai makna sesuai dengan konteksnya.
Seperti terbaca di atas, ayat-ayat yang berbicara tentang pengangkatan khalifah dalam Al-Quran ditujukan kepada Nabi Adam dan Nabi Daud. Khalifah pertama adalah manusia pertama (Adam) dan ketika itu belum ada masyarakat manusia, berbeda dengan keadaan pada masa Nabi Daud. Beliau menjadi khalifah setelah berhasil membunuh Jalut.
Al-Quran dalam hal ini menginformasikan bahwa,
Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah, (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan) atas semesta alam. (Tafsir QS Al-Baqarah [2]: 251].
Ayat ini menunjukkan bahwa Daud memperoleh kekuasaan tertentu dalam mengelola satu wilayah, dan dengan demikian kata khalifah pada ayat yang membicarakan pengangkatan Daud adalah kekhalifahan dalam arti kekuasaan mengelola wilayah atau dengan kata lain kekuasaan politik. Hal ini didukung pula oleh surat Al-Baqarah (2): 251 di atas yang menjelaskan bahwa Nabi Daud a.s. dianugerahi hikmah yang maknanya telah dijelaskan sebelum ini.
Kekhalifahan dalam arti kekuasaan politik dipahami juga dari ayat-ayat yang menggunakan bentuk jamak khulafa’. Perhatikan konteks ayat-ayat surat Al-A’raf (7): 69 dan 74, serta Al-Naml (27): 62.
Menarik juga untuk dibandingkan bahwa ketika Allah menguraikan pengangkatan Adam sebagai khalifah, digunakan bentuk tunggal dalam menunjuk pengangkatan itu,
Sesungguhnya Aku akan mengangkat di bumi khalifah (Tafsir QS Al-Baqarah [2]: 30).
Sedangkan ketika berbicara tentang pengangkatan Daud sebagai khalifah digunakannya bentuk plural (jamak),
Sesungguhnya Kami telah mengangkat engkau khalifah.
Pengggunaan bentuk tunggal pada Adam cukup beralasan karena ketika itu memang belum ada masyarakat manusia, apalagi ia baru dalam bentuk ide. Perhatikan redaksinya yang menyatakan, “Aku akan”. Sedangkan pada Daud, digunakan bentuk jamak serta past tense (kata kerja masa lampau), “Kami telah” untuk mengisyaratkan adanya keterlibatan selain dari Tuhan (dalam hal ini restu masyarakatnya) dalam pengangkatan tersebut. Di sisi lain dapat dikatakan bahwa mengangkat seseorang sebagai khalifah boleh-boleh saja dilakukan oleh satu oknum, selama itu masih dalam bentuk ide. Tetapi kalau akan diwujudkan di alam nyata maka hendaknya ia dilakukan oieh orang banyak atau masyarakat.
Ayat Sesungguhnya Aku akan mengangkat khalifah di bumi (Tafsir QS Al-Baqarah 12]:31) menginformasikan juga unsur-unsur kekhalifahan sekaligus kewajiban sang khalifah. Unsur-unsur tersebut adalah
(1) bumi atau wilayah,
(2) khalifah (yang diberi kekuasaan politik atau mandataris), serta
(3) hubungan antara pemilik kekuasaan dengan wilayah, dan hubungannya dengan pemberi kekuasaan (Allah Swt.).
Kekhalifahan itu baru dinilai baik apabila sang khalifah memperhatikan hubungan-hubungan tersebut.
b. Isti’mar
Kata isti’mar dalam bahasa Arab modern diartikan penjajahan; ista’mara adalah menjajah. Makna ini tidak dikenal dalam bahasa Al-Quran, dan memang ia merupakan penamaan yang tidak sejalan dengan kaidah bahasa Arab dan akar katanya.
Dalam surat Hud (11): 61 Allah berfirman:
Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”
Kata isti’mara pada ayat di atas terdiri dari huruf sin dan ta’ yang dapat berarti meminta seperti dalam kata istighfara, yang berarti meminta maghfirah (ampunan). Dapat juga kedua huruf tersebut berarti “menjadikan” seperti pada kata hajar yang berarti “batu” bila digandengkan dengan sin dan ta’, sehingga terbaca istahjara yang maknanya adalah menjadi batu.
Kata ‘amara dapat diartikan dengan dua makna sesuai dengan objek dan konteks uraian ayat. Surat Al-Taubah (9): 17 dan 18 yang menggunakan kata kerja masa kini ya’muru, dan ya’muru dalam konteks uraian tentang masjid diartikan memakmurkan masjid dengan jalan membangun, memelihara, memugar, membersihkan, shalat, atau i’tikaf di dalamnya. Sedangkan surat Al-Rum (30):9 yang mengulangi dua kali kata kerja masa lampau ‘amaru berbicara tentang bumi, diartikan sebagai membangun bangunan, serta mengelolanya untuk memperoleh manfaatnya.
Jika demikian, kata ista’marakum dapat berarti “menjadikan kamu” atau “meminta/ menugaskan kamu” mengolah bumi guna memperoleh manfaatnya. Dari satu sisi, penugasan tersebut dapat merupakan pelimpahan kekuasaan politik; di sisi lain karena yang menjadikan dan yang menugaskan itu adalah Allah Swt., maka para petugas dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan kehendak yang menugaskannya.
PRINSIP-PRINSIP KEKUASAAN POLITIK
Seperti terlihat di atas, kekuasaan politik dianugerahkan oleh Allah Swt.kepada manusia. Penganugerahan ini dilakukan melalui satu ikatan perjanjian. Ikatan ini terjalin antara sang penguasa dengan Allah Swt. di satu pihak dan dengan masyarakatnya di pihak lain. Perjanjian dengan Allah dinamai oleh-Nya dalam Al-Quran dengan ‘ahd.
Dalam surat Al-Baqarah (2):124 Nabi Ibrahim a.s. yang diangkat Tuhan menjadi imam bermohon kepada-Nya agar imamah (kepemimpinan) itu diperoleh pula oleh anak cucunya. Kemudian Allah menjawab:
Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang dzalim“.
Adapun perjanjian dengan anggota masyarakat, maka ia dinamai bai’at. Hal ini telah penulis isyaratkan sebelum ini ketika menjelaskan sebab penggunaan kata Kami dalam pengangkatan Nabi Daud a.s. sebagai khalifah, dan diisyaratkan juga oleh Al-Quran terhadap Nabi Muhammad Saw. yang kepada beliau datang wanita-wanita untuk berbaiat.
Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Tafsir QS Al-Mumtahanah (60): 12).
Perjanjian ini -baik antara sang penguasa dengan masyarakat maupun antara dia dengan Yang Mahakuasa- merupakan amanat yang harus ditunaikan. Dari sini, tidak heran jika perintah taat kepada penguasa (ulil amr) didahului oleh perintah menunaikan amanah. Perhatikan firman Allah berikut:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Tafsir QS Al-Nisa’ [4]: 58-59).
Kedua ayat di atas dinilai oleh para ulama sebagai prinsip-prinsip pokok yang menghimpun ajaran Islam tentang kekuasaan atau pemerintahan.
Amanat dimaksudkan berkaitan dengan banyak hal, salah satu di antaranya adalah perlakuan adil. Keadilan yang dituntut ini bukan hanya terhadap kelompok, golongan, atau kaum Muslim saja, tetapi mencakup seluruh manusia bahkan seluruh makhluk.
Ayat-ayat Al-Quran yang menyangkut hal ini amat banyak, satu di antaranya berupa teguran kepada Nabi Saw. yang hampir saja menyalahkan seorang Yahudi karena terpengaruh oleh pembelaan keluarga seorang pencuri. Dalam konteks inilah turun firman Allah:
Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat, (Tafsir QS Al-Nisa’ [4]: 105).
Nabi Saw. dalam sekian banyak hadisnya memperingatkan hal tersebut, antara 1ain sabdanya,
(Berhati-hatilah) Doa orang yang teraniaya diterima Allah, walaupun ia durhaka, (karena) kedurhakaannya dipertanggunjawabkan oleh dirinya sendiri (HR Ahmad dan Al-Bazzar melalui Abu Hurairah).
Berdampingan dengan amanat yang dibebankan kepada para penguasa, ditekankan kewajiban taat masyarakat terhadap mereka.
Perlu diperhatikan bahwa redaksi ayat di atas menggandengkan kata “taat” kepada Allah dan Rasul, tetapi meniadakan kata itu pada ulil amr.
Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan ulil amr antara kamu (Tafsir QS Al-Nisa’ [4]:59).
Tidak disebutkannya kata taat pada ulil amr untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini dikenal kaidah yang sangat populer yaitu,
Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah).
Tetapi di sisi lain, apabila perintah ulul amr tidak mengakibatkan kemaksiatan, maka ia wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak disetujui oleh yang diperintah.
Seorang Muslim wajib memperkenankan dan taat menyangkut apa saja (yang diperintahkan ulul amr), suka atau tidak suka, kecuali bila ia diperintahkan berbuat maksiat, maka ketika itu tidak boleh memperkenankan, tidak juga taat.(Diriwayathan oleh Bukhari Muslim, dan lain-lain melalui Ibnu Umar).
Taat dalam bahasa Al-Quran berarti “tunduk” menerima secara tulus dan menemani. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekadar melaksanakan apa yang diperintahkan tetapi harus ikut berpartisipasi dalam upaya-upaya yang dilakukan penguasa politik guna mendukung usaha-usahanya.
Dalam konteks ini, Nabi Saw. bersabda:
Agama adalah nasihat.
Dan ketika para sahabat bertanya, “Untuk siapa?” Nabi Saw. menjawab antara lain,
Untuk para pemimpin kaum Muslim dan khalayak ramai mereka (HR Muslim melalui sahabat Nabi Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Addari).
“Nasihat” yang dimaksud Nabi di sini adalah dukungan positif kepada mereka termasuk kontrol sosial demi suksesnya tugas-tugas yang mereka emban. Ayat Al-Nisa’ yang dikutip di atas menurut pakar tafsir Al-Maraghi. menjelaskan prinsip-prinsip ajaran agama dalam bidang pemerintahan serta sumber-sumbernya, yaitu:
1. Al-Quran Al-Karim yang ditunjuk oleh perintah agar taat kepada Allah.
2. Sunnah Rasul Saw. yang ditunjuk oleh kewajiban taat kepada Rasul.
3. Konsensus ulul amr, yakni mereka yang diberi kepercayaan oleh umat seperti para ulama, cerdik cendekia, pemimpin militer, penguasa, petani, industriawan, buruh, wartawan, dan sebagainya. Mereka itulah ulul amr.
4. Mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada kaidah-kaidah umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah.
TUGAS-TUGAS PARA PENGUASA
Mereka yang mendapat anugerah “menguasai wilayah” diberi berbagai tugas, yang antara lain diuraikan oleh surat Al-Hajj (22): 41:
Orang-orang yang jika Kami kukuhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah yang munkar, dan kepada Allah kesudahan segala urusan. (Tafsir QS Al-Hajj [22]: 41).
“Mendirikan shalat” adalah lambang hubungan baik dengan Allah, sedang “menunaikan zakat” adalah lambang perhatian yang ditujukan kepada masyarakat lemah. “Amr ma’ruf” mencakup segala macam kebajikan, adat istiadat, dan budaya yang sejalan dengan nilai-nilai agama, sedang nahi an al-munkar adalah lawan dari amr ma’ruf.
Dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya, para penguasa dituntut untuk selalu melakukan musyawarah, yakni “bertukar pikiran dengan siapa yang dianggap tepat guna mencapai yang terbaik untuk semua.” Mereka juga dituntut untuk memanfaatkan semua potensi yang dapat dimanfaatkan guna mencapai hasil maksimal yang diharapkan. Dalam konteks ini, terjadi diskusi di kalangan ulama, berkaitan dengan keterlibatan non-Muslim dalam pemerintahan. Diskusi ini muncul baik ketika menafsirkan kata minkum (dari golongan kamu orang-orang Mukmin) pada surat Al-Nisa (4): 58 yang berbicara tentang ulil amr maupun dalam ayat-ayat lain yang secara tekstual melarang mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai auliya’ (yang biasa diterjemahkan pemimpin-pemimpin). Misalnya firman Allah: (Ayat ini diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama dalam Al-Quran dan Terjemahnya sebagai berikut):
Hai orang-orang Mukmin, janganlah kamu mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu yang mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim (QS Al-Ma-idah [5]: 51).
Al-Quran tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin kerja sama apalagi mengambil sikap tidak bersahabat. Al-Quran memerintahkan agar setiap umat berpacu dalam kebajikan seperti yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah (2): 148:
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Bahkan Al-Quran sama sekali tidak melarang kaum Muslim untuk berbuat baik dan memberi sebagian harta mereka kepada siapa pun, selama mereka tidak memerangi dengan motif keagamaan atau mengusir kaum Muslim dan kampung halaman mereka (QS Al-Mumtahanah [60]: 8).
Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (Tafsir QS Al-Mumtahanah [60]: 8).
Demikian sekilas tentang prinsip-prinsip dasar wawasan Al-Quran tentang politik. Rincian dan setiap kebijaksanaan politik tidak boleh bertentangan dengan prinsip di atas.
—————-
Disarikan dari WAWASAN AL-QURAN Bab Politik
Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat
Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A.



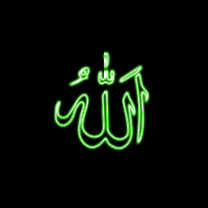
Tinggalkan komentar